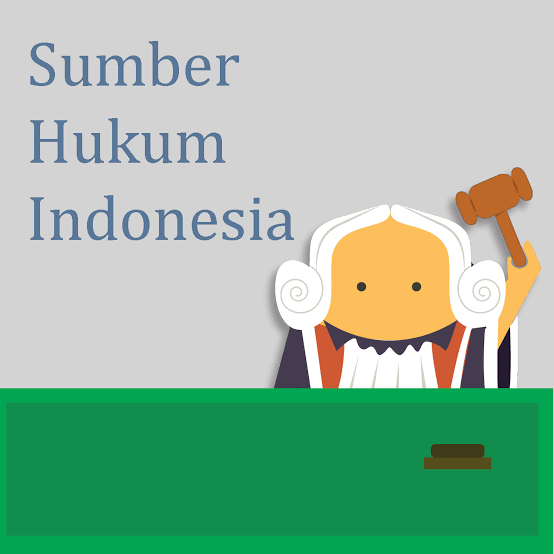A. PERIODE PENJAJAHAN
1. MASA PENJAJAHAN BELANDA
sejarah hukum islam di Indonesiasangatlah panjang, diakuinya hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Hukum Islam diakui di Indonesia sejak datangnya Islam ke Indonesia jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat terkait kapan datangnya Islam ke Indonesia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 M, hal ini didasarkan pada adanya pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia dan India yang sudah sampai ke kepulauan nusantara.
Pendapat lain menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada Abad ke-13 Masehi, hal ini ditandai oleh sudah adanya masyarakat muslim di Samudra Pasai, Perlak dan Palembang. Sementara di Jawa terdapat makam Fatimah Binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 475 H atau 1082 M, dan makam-makam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13. Hal ini merupakan bukti perkembangan komunitas Islam termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu yakni Majapahit.
Sejarah Hukum Islam di Indonesia Pada akhir abad keenam belas atau tepatnya tahun 1596, organisasi perusahaan Belanda bernama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Maksudnya semula untuk berdagang, namun kemudian berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Belanda memberi kekuasaan kepada VOC untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Karena hak yang diperolehnya itu, VOC mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai badan pemerintahan. Sebagai usaha memantapkan pelaksanaan kedua fungsi itu, VOC mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Untuk itu di daerah-daerah yang dikuasainya kemudian, VOC membentuk badan-badan peradilan untuk Bangsa Indonesia. Namun, oleh karena susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda itu tidak dapat berjalan dalam praktik, maka VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya.
Pada waktu VOC pertama kali menguasai Indonesia kurang menghiraukan agama dan kebudayaan bangsa Indonesia. Setelah kekuasaan kompeni diambil oleh kerajaan belanda abad ke-18 barulah ada perhatian Belanda kepada kehidupan kebudayaan dan agama. Belanda selalu kuatir dan curiga terhadap perkembangan Islam di Indonesia terutama karena ada gerakan Pan Islamisme yang berpusat di Turki semasa kekuasaan Othmaniyah di Istambul. Pemerintah Kerajaan Belanda mengalami perlawanan politik dan militer dari kesultanan-kesultanan dan pemimpin-pemimpin ummat Islam di daerah-daerah Indonesia terutama sepanjang abad ke-19 dan yang terakhir adalah perang Aceh yang baru dapat berakhir (formil) pada tahun 1903, jadi sudah masuk abad ke-20 bahkan pada tahun 1908 di Kamang Sumatera Barat terjadi lagi pemberontakan rakyat muslimin terhadap Belanda. Oleh karena itu Belanda memperhatikan psikologi massa antara lain dengan membiarkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.
Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan sewaktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) yang mana Thomas S. Raffles menjadi Gubernur Jendral Inggris untuk kepulauan Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam.
Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori receptio in complexu yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Daerah jajahan Belanda yaitu Indonesia dengan ibu kotanya Batavia dalam hal kekuasaan administrasi pemerintahan dan peradilan, termasuk peradilan agama sepenuhnya ditangan Residen. Residen dengan aparat kepolisiannya berkuasa penuh menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang terjadi.
Pada masa pemerintahan Van Den Berg inilah hukum Islam benar-benar diakui berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat yang beragama Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat (3) Regeerings Reglement yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam, oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam gonsdientig wetten dan kebiasaan mereka. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan pengadilan agama yang kemudian diiringi dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama (mahkamah syar’iyyah). Munculnya teori Receptio In Complexu ini menjadikan hukum Islam diakui dan berlaku sebagai hukum positif pada masa pemerintahan Hindia Belanda walaupun pada dasarnya hukum Islam telah ada berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda tiba di Indonesia.
Namun kemudian,Teori receptio in complexu kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu teori receptie (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Oleh karenanya menurut teori tersebut seperti hukum kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat. Munculnya teori receptie ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.
Hindia Belanda sebagai realisasi teori receptie ini adalah dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara:
- Sama sekali tidak memasukkan masalah hudud dan qishash dalam bidang hukum pidana. Mengenai hukum pidana ini telah diunifikasi dengan Wet Boek Van Strafrecht yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (Staatsblad 1915 No. 732).
- Dibidang tatanegara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali. Segala bentuk kajian yang berhubungan dengan politik ketatanegaraan (siyasah) dilarang keras.
- Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan.
Hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:
- Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat);
- Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.
Adanya teori resepsi ini yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat yang dalam realisasinya dikeluarkan Staatsblad 1937 No. 116 yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama menjadikan peranan hukum Islam sangat dibatasi. Pada saat itu hukum Islam mengalami kondisi yang sangat berat karena harus berhadapan dengan hukum adat dan hukum pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu. Dampaknya adalah hukum Islam yang telah berlaku secara formal dipersempit ruang geraknya oleh pemerintah Hindia Belanda seperti wewenang menyelesaikan hukum waris yang sebelumnya menjadi wewenang pengadilan agama dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri.
2. MASA PENJAJAHAN JEPANG
Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia sebagai akibat pecahnya perang Pasifik. Kedatangan Jepang mula-mula disambut dengan senang hati bangsa Indonesia karena telah mengusir Belanda yang telah ratusan tahun menguasai Indonesia. Kebijakan yang ditempuh Jepang yaitu berusaha merangkul pemimpin Islam untuk diajak bekerja sama. Dia mengklaim dirinya sebagai saudara tua rakyat Indonesia. Tujuannya untuk memobilisasi seluruh penduduk dalam rangka untuk mempercepat tercapainya tujuan-tujuan perang. Kelanjutan dari kebijakan politiknya secara bertahap yaitu Jepang mengakui kembali organisasi-organisasi Islam yang sebelumnya telah dibekukan. Selain itu Jepang memberi motivasi kepada kalangan Islam untuk mendirikan organisasi-organisasi Islam baru. Dalam sejarah modern Indonesia, Jepang tercatat sebagai pemerintah pertama yang memberi tempat penting kepada golongan Islam.
Beberapa alasan Jepang mengesahkan pendirian ormas-ormas Islam yaitu:
- Untuk memperoleh dukungan dan bantuan dari penduduk di pedesaan diperlukan organisasi yang dipatuhi penduduk yaitu organisasi para ulama.
- Dengan pengesahan secara formal lebih mempermudah Jepang untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi-organisasi Islam.
- Jepang tidak berhasil mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia dengan pengakuannya terhadap fungsi putra dan Jawa Hokokai.
- Jepang bermaksud menebus dosa beberapa kesalahannya terhadap kalangan Islam.
Pada awal kekuasaannya, Jepang membentuk Shumubu (Kantor Departemen Agama) di Ibukota Jakarta, selanjutnya membentuk Hizbullah, semacam unit militer bagi pemuda Islam dan didirikannya organisasi federasi Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Terwadahinya para ulama dan para pemuda Islam membuat Jepang tidak menaruh kecurigaan kepada para pemimpin Islam. Dalam kondisi itulah para ulama dengan bebas dapat menyebarluaskan hukum Islam keberbagai lapisan masyarakat.
Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya (masa kolonial Belanda). Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1. hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut “Sooryoo Hooim” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “kaikyoo kootoohoin”.
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tersebut cukup menguntungkan masyarakat Islam walaupun dibalik itu maksud tujuan Jepang adalah hanya untuk mencari simpati dan dukungan rakyat Indonesia semata. Kebijakan Jepang cukup menguntungkan karena adanya beberapa kebebasan yang diberikan seperti diakuinya kembali organisasi-organisasi Islam dan membentuk organisasi Islam yang baru seperti Hizbullah yaitu semacam unit militer bagi pemuda Islam dan didirikannya organisasi federasi Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang mana kebijakan itu tidak diberikan pada waktu pemerintahan Hindia Belanda. Namun kebijakan tersebut tidak diikuti pada kebijakan peradilan agama karena kebijakan yang dikeluarkan hanya merubah nama dalam peradilan agama tetapi isinya sama dengan kebijakan sewaktu pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan Jepang tidak banyak memberikan pengaruh bagi kondisi perkembangan hukum Islam karena singkatnya waktu Jepang menguasai Indonesia menyusul kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
B. MASA KEMERDEKAAN
1. ORDE LAMA
Perjuangan mengangkat hukum Islam juga dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam pada saat menjelang kemerdekaan. Hasilnya adalah disetujuinya rumusan kompromi yang dituangkan dalam PiagamJakarta (Jakarta Charter) dengan tambahan rumusan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun dalam persidangan-persidangan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) selanjutnya perjuangan tersebut mengalami kemunduran. Keinginan-keinginan golongan Islam yang telah diajukan sebelumnya semuanya ditolak, bahkan setelah proklamasi kemerdekaan, tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang menjadi simbol kemenangan Islam dihapuskan, kata Allah dalam Mukaddimah diganti dengan Tuhan dan kata Mukaddimah diubah menjadi pembukaan.
Salah satu makna kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia adalah terbebas dari pengaruh hukum Belanda. Menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwayakni dengan lahirnya ideologi “Nasakom” yang menyatukan paham “nasionalis, agama, dan komunis”. Tindakan tersebut sangat tidak masuk akal karena Islam sebagai agama tauhid tidak mungkin bisa disatukan dengan komunis. Karena itu tindakan tersebut mendapat reaksi yang keras dari pemimpin-pemimpin Islam waktu itu sehingga tidak bisa dikembangkan dan dalam waktu dekat ideologi ini terkubur dengan sendirinya.
Dunia peradilan agama juga berada dalam keadaan suram disebabkan oleh tetap diberlakukannya lembaga ekskutorial verklaring artinya setiap putusan pengadilan agama baru mempunyai kekuatan hukum berlaku setelah mendapat pengukuhan (fat eksekusi) dari pengadilan negeri. Hal itu menjadikan pengadilan agama selalu berada dalam posisi di bawah pengadilan negeri karena dapat berlaku atau tidaknya putusan-putusan pengadilan agama tergantung kepada pengadilan negeri. Di samping itu, pengadilan agama dicabut kewenangannya sejak tahun 1937 dan diteruskan pada masa orde lama khususnya masalah kewarisan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa sepanjang mengenai warisan diseluruh Indonesia, hukum yang adat harus didahulukan yakni di daerah-daerah yang amat kuat pengaruh Islamnya, karena sedikit banyak sudah mencakup unsur-unsur hukum Islam. Oleh karena itu wewenang menjatuhkan keputusan (sepanjang) mengenai warisan berada pada pengadilan negeri biasa. Pembatasan lain yang menjadi masalah dalam penerapannya yaitu pengadilan agama hanya diberi wewenang untuk memutus perkara apabila kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat beragama Islam. Masalah yang timbul yakni siapa saja yang dimaksudkan sebagai orang Islam yang dalam hal ini Notosusanto memberikan kriteria bahwa yang termasuk orang Islam adalah sebagai berikut:
- Seorang yang termasuk bagian dari kaum muslimin menurut pandangan sesama warga negara. Ia tidak menolak disebut orang Islam termasuk melangsungkan perkawinan secara Islam dan menginginkan dikubur secara Islam jika meninggal dunia.
- Orang yang dengan sukarela telah mengucapkan dua kalimat syahadat.
- Orang yang tidak sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi juga memiliki pengetahuan ajaran-ajaran pokok Islam.
- Orang yang tidak sekadar memiliki pengetahuan ajaran-ajaran pokok Islam, tetapi juga menjalankan kewajiban keagamaan khususnya shalat dan puasa.
Pada masa orde lama ini, kondisi hukum Islam belum menandakan adanya perbaikan bahkan menurut Warkum Sumitro pada masa itu hukum Islam berada pada masa yang amat suram. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan hukum agama selalu dikendalikan oleh manifesto politik, adanya kebijakan yang tidak berpihak terhadap organisasi-organisasi Islam yang dinilai memiliki peran besar dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, bahkan lahirnya ideologi “Nasakom” yang menyatukan paham “nasionalis, agama, dan komunis”.
2. ORDE BARU
Runtuhnya kekuasaan Orde Lama memberikan harapan baru bagi umat Islam untuk memantapkan keberadaan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Namun harapan pada awal orde baru ini juga disertai dengan kekecewaan baru karena ternyata setelah pemerintah Orde Baru memantapkan kekuasaannya, mereka segera melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap kekuatan politik Islam, terutama para kelompok radikal yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pihak pemerintah. Pengawasan terhadap politik Islam tersebut terus diperketat bahkan disertai dengan isu-isu sensitif trauma masa lalu tentang pembangkangan pemimpin-pemimpin Islam.
Memperhatikan sikap pemerintah yang semakin ketat dalam pengawasan partai-partai politik seperti itu, para pemimpin Islam sadar bahwa perjuangan untuk menegakkan hukum Islam melalui jalur politik tidak selamanya berhasil, bahkan resikonya lebih tinggi. Karena itu para pemimpin Islam mulai “berubah haluan” perjuangan yang semula untuk mewujudkan suatu negara Islam berubah menjadi perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam. Perjuangan untuk mewujudkan hukum Islam di Indonesia yang semula dipandang sebagai suatu perjuangan untuk memproklamasikan suatu negara Islam secara formal berubah menjadi perjuangan kultural dari bawah yakni dengan berusaha keras melakukan penerapan praktis dari hukum Islam dengan tetap bertitik tolak pada “Piagam Jakarta”. Di dalam perkembangannya, perjungan untuk mengangkat unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional tetap dilakukan oleh kelompok masyarakat muslimin. Adapun bidang-bidang hukum Islam yang diperjuangkan waktu itu yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan, hibah, wakaf, dan hukum zakat. Diantara bidang-bidang hukum yang diperjuangkan itu hanya bidang hukum perkawinan yang dapat dikatakan berhasil dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut pendapat Hazairin dan Mahadi merupakan ajal bagi kematian teori receptie. Karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini menurut Daud Ali, bahwa sejak lahirnya undang-undang perkawinan nasional itu, maka:
- Hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah perkawinan sah atau tidak,
- Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum Barat,
- Negara Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam.
Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Kompilasi Hukum Islam tidak dihasilkan melalui proses legislasi dewan perwakilan rakyat sebagaimana peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagas oleh mahkamah agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya.[4]
Kebijakan pemerintah pada masa orde baru terhadap hukum Islam juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pada masa orde baru, pemerintah membatasi dan memperketat pengawasan terhadap aktifitas gerakan politik Islam karena dikhawatirkan akan menandingi kekuatan pemerintah. Karena itu terjadi perubahan perjuangan oleh para tokoh-tokoh Islam yang semula ingin mewujudkan negara Islam berubah menjadi perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam.
Perubahan arah perjuangan tersebut diantaranya yaitu bagaimana berjuang mengangkat unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara praktis dan secara hukum adalah sah. Perjungan tersebut akhirnya berhasil yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menurut Hazairin dan Mahadi dengan lahirnya undang-undang ini merupakan ajal bagi kematian teori receptie karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan hukum Islam secara otomatis berlaku tanpa harus melalui hukum adat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menandakan hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia, walaupun baru di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.
3. ERA REFORMASI DAN SEKARANG
Sejarah era reformasi lahir sejak tahun 1998 yaitu dengan jatuhnya rezim pemerintahan orde baru yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sejak jatuhnya rezim pemerintahan orde baru tersebut, terjadi perubahan yang sangat besar dalam diri bangsa Indonesia termasuk diantaranya dalam wilayah hukum. Pada era reformasi, isu hukum menjadi salah satu isu yang sangat penting hingga terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berpengaruh besar terhadap kebijakan politik dan hukum Indonesia sampai sekarang ini.
Pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia diatur dalam GBHN tahun 1999. Dengan berlakunya GBHN tahun 1999 ini, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku hukum nasional.[5] Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang yaitu hukum adat, Barat dan Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, bukan pemaksaan 119
Partisipasi masyarakat dalam hukum nasional dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 53 undang-undang tersebut menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”. Ini berarti bila masyarakat menghendaki, maka hukum Islam dapat diajukan menjadi rancangan undang-undang atau perda untuk menjadi hukum nasional. Di samping itu, dalam RPJPN 2005-2025 juga dinyatakan bahwa kemajemukan tatanan hukum yang berlaku di masyarakat harus diperhatikan dalam pembaruan materi hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam sebagai hukum yang tumbuh dimasyarakat juga tidak boleh diabaikan. Memang pemanfaatan hukum Islam sebagai bahan baku pembentukan hukum nasional agak diabaikan oleh RPJMN 2004-2009. Namun demikian, RPJMN tidak mungkin menolak ketika aspirasi masyarakat menunjukkan akan keinginan untuk diperhatikannya hukum Islam bagi pembentukan hukum nasional, apalagi RPJMN hanya berlaku selama 5 tahun.120
Sejak bergulirnya era reformasi, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai hukum Islam. Kondisi Islam pada masa era reformasi juga menunjukkan tanda-tanda positif.
Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang diantaranya yaitu:
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankkan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Disamping berbagai undang-undang di atas, pada masa reformasi juga muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam di daerah-daerah.Fenomena perda bernuansa syariat merupakan dampak dari perubahan sistem politik kenegaraan dan pemerintahan. Sistem politik yang otoritarian berubah menjadi demokratis. Sistem pemerintahan yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan tuntutan masyarakat dan telah ditampung dalam Amandemen UUD 1945. Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pengaturan Anggaran Daerah dan Pusat menjadikan pemerintah daerah lebih otonom. Otonomi daerah inilah yang mengakibatkan munculnya perda-perda yang banyak bernuansa syariah. Para politisi muslim menjadi motor penggerak lahirnya perda-perda itu.
Banyaknya undang-undang dan peraturan daerah yang bernuansakan hukum Islam di Indonesia pada era reformasi sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Indonesia sangat besar agar hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif. Hal ini ini terjadi karena kebijakan politik dan hukum pemerintah pada era reformasi ini memungkinkan terjadinya hal tersebut. Pada era reformasi ini juga muncul berbagai organisasi-organisasi Islam yang ikut meramaikan perjuangan.
C. POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber disini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam system peradilan agama, sepeti selama ini. Namun juga dalam sistrm peradilan (meliputi materi hukum dan system kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks ini menempatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fiqh atau hukum islam menjadi sumber kajian dalam dunia ilmu hukum dan sekaligus sumber hukum materiil. Namun bahwa fiqh yang ada disini harus berupa fiqh yang memang sudah sesuai dengan tuntunan zaman, bukan dalam pengertian pasif dan jumud.
Bukan pula hanya sekedar mentransfer fiqh yang merupakan produk beberapa abad lalu. Tapi juga tidak berarti harus membuang begitu saja hasil pemikirran fuqaha masa yang sudah silam. Pemikiran atau karya fuqaha’ masa lalu merupakan living knowledge (pelajaran hidup) yang sangat berarti bagi pemikiran masa kini. Bahkan juga tidak mustahil kalau juga menjadi sumber pemikiran sekarang, sebagai proses historical continuity dalam tradisi akademik.
Kalau menempatkan fiqh atau hukum islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam tataran operasional atau hukum materiil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur atau alur, anatara lain sebagai berikut:[6]
- Peraturan perundang-undangan.
- Sumber kebijakan pelaksana pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagai mana peraturan pemerintah, namun dalam konteks kedisiplina n secara administrative, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan nilai-nilai legislasi pula.
- Yurisprudensi.
- Sumber bagi penegak hukum,polisi, jaksa, dan pengacara.
- Sumber ilmu hukum atau filsafat hukum.
- Sumber nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan.
Dari uraian diatas, dapatlah kita katakana bahwa lahirnya reformasi total di Indonesia menjadi kesempatan dan sekaligus tantangan bagi kajian hukum Islam. Kalau semula kajian hukum Islam seoalah melangit atau ngawang-ngawang, oleh karena didominasi oleh model menghafal hasil pemikiran ulama yang telah sekian abad lalu, kini kajian hukum islam sudah saatnya untuk mampu bersifat empiris dan realistis (membumi yang mudah dipahami dan kemudian diamalkan oleh pemeluknya). Para pemikir hukum islam dituntut untuk mempu meletakan hukum islam untuk mampu berperan dan berdaya guna dalam rangka keperluan kehidupan umat islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Disini ada peluang besar sekali bagi kedudukan hukum Islam, namun juga sekaligus tantangan kemampuan para pelaku kajiannya. Konsekuensinya, model dan kajian pendekatan hukum islam di Indonesia, terutama sekali di lembaga-lembaga akademik seperti PT dan pusat kajian, sudah waktunya untuk diperbaharui. Model, pendekatan dan filosofi kajian hukum Islam atau fiqh di IAIN, STAIN, PTAIS perlu diadakan reorientasi atau bahkan perubahan agar benar-benar bermanfaat dan memenuhi tuntutan tadi.. ini meliputi merekonstruksi pemikiran hukum islam dengan bahasa UU, seperti KHI, sehingga akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan bahasa hukum pada umumnya. Usaha positivisasi hukum islam merupakan suatu keharusan baik dalam konteks kajian akademik yang selalu mengikuti ekelektisisme maupun proses demokratisasi yang mendasarkan pada mayoritas penduduk. Pada akhirnya menjadi tantangan bahwa islam harus mampu menunjukan janji besarnya, yaitu rahmatan lil alamin danli al-tahqiq mashalih al nas. Inilah tantangan bagi para ahli hukum islam dan sekaligus bagi para ahli hukum umum.
D. Pemahaman Fatwa dan Macam-Macamnya
Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab: al-fatwa, yang merupakan bentuk masdar fata, yaftu, fatwan yang artinya muda, baru, atau penjelasan (Ma’ruf Amin, 19:2007). Imam Ibnu Mandzur (145: Juz 15) dalam Lisaan al-Arab menyatakan, aftaahu fi al-amr abaanahu lahu(menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). Wa aftaa al-rajulu fi al-mas`alah (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). wa astaftaituhu fiihaa fa aftaaniy iftaa`an wa futaa (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)”. Pendapat lainnya menyatakan bahwa fatwa berasal dari kata al-fatwa atau al-futya yang artinya jawaban terhadap suatu persoalan. Secara terminologi, fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok (Ma’ruf Amin, 20:2007). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, Al-fatwa berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminita fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tesebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminita fatwa disebut al-mustafti.
Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam sengaja didesain untuk menjelaskan persoalan-persoalan secara global. Sementara, untuk merinci dan memberikan petunjuk pelaksanaan suatu ajaran (hukum), inilah tugas Rasulullah untuk menjelaskannya dengan ucapan, perbuatan, dan penetapannya, yang kemudian kita sebut sebagai Hadits atau Sunnah Nabi. Namun, persoalan yang dijelaskan Nabi kebanyakan hanya terkait bidang ibadah. Sementara, dalam bidang muamalah, pada umumnya, Nabi tidak banyak memberikan rincian yang bersifat aplikatif, karena bidang muamalah senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, di samping juga dipengaruhi adat istiadat setempat. Maka, untuk mengantisipasi perubahan itu, Allah telah memberikan sarana yang memungkinkan umat manusia untuk terus menjalankan ajaran Islam, melalui sebuah proses bernama ijtihad. Ijtihad adalah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Hadits untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Menurut al-Syaukani (250: tt) kata ijtihad berakar dari kata al-Juhd, yang berarti al-Thaqat (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-Jahd yang berarti al-Musyaqat (kesulitan,kesukaran). Jadi menurutnya ijtihad mempunyai artibadzl al-Wus’ wa al-Majhud (pengerahan daya dan kemampuan). Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahawa Ijtihad adalah sebuah upaya pengerahan segala daya dan kemampuan dalam mencarikan jalan keluar berbagai persoalan yang berat dan sulit. Ijtihad tidak semata-mata identik dengan aktifitas berfikir, tetapi juga tanggung jawab dan kepercayaan atas proses dan hasil dari ijtihadnya.
Sementara Ahmad Fayyumi (30-32, Juz III: tt) dalam kamusnya membedakan antara al-Jahdu dan al-Juhdu. Ia menuliskan: “al-Juhd”adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Hijaz sementara kata al-Jahddipakai oleh selain Arab Hijaz. Al-Jahd memiliki arti mengerahkan segenap kemampuan. Sementara kata al-Juhd mengandung makna kesulitan.” Memahami arti yang disampaikan para ahli bahasa terlihat ada perbedaan dalam memaknai akar kata ijtihad. Namun bila diteliti lebih dalam lagi sebenarnya tidak ada perbedaan di sana. Kata al-Jahdu yang memiliki arti mengerahkan segenap kemampuan tidak akan pernah dilakukan oleh seseorang bila tidak menemui sebuah kesulitan. Artinya kedua kata ini saling melengkapi. Setiap kesulitan akan dihadapi dengan segenap kekuatan yang dimiliki sebagaimana segenap kekuatan hanya akan dikeluarkan bila menghadapi kesulitan. Raghib Al-Isfahani (110: tt) dengan indah mengartikan kata ijtihad dengan menggabungkan dua unsur tersebut. Beliau menuliskan, “wa al- Ijtihadu Akhdzun Nafsi bi Badzl al- Thoqoti wa Tahammuli al- Masyaqqoh’ (Ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan segala kemampuan yang dimiliki dan menanggung semua kesulitan yang ada). Dari berbagai pengertian ijtihad di atas, penjelasan al-Syirazi seperti dikutip Qadri Azizy (46: 2004) merepresentasikan pengertian ijtihad yang sederhana dan mudah dipahami, yaitu menghabiskan kekuatan kemampuan dan mencurahkan daya upaya untuk memperoleh (menemukan) hukum syari’.
Ijtihad ini menjadi sarana penting untuk menjawab persoalan-persoalan yang belum tercakup secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits. Karenanya, diperlukan persyaratan yang ekstra ketat bagi seseorang (ulama) untuk melakukan ijtihad (menjadi mujtahid), dan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat para mujtahid. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penetapan fatwa harus didasarkan pada prinsip-prinsip ijtihad, yakni fahm al-Nash (memahami nash) dan fahm al-Waaqi’ al-Haaditsah” (memahami realitas yang terjadi). Fahmu al-nash adalah upaya memahami dalil-dalil syariat hingga diketahui dilalah al-hukm (penunjukkan hukum) yang terkandung di dalam dalil tersebut. Sedangkan fahmu al-waaqi’ al-haaditsah adalah upaya mengkaji dan meneliti realitas yang hendak dihukumi agar substansi persoalannya bisa diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas tersebut. Dengan persyaratan yang begitu ketat, maka tidak semua orang bisa melakukan ijtihad.
Salah satu pranata atau jalan yang disiapkan hukum Islam bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah dengan bertanya atau memohon penjelasan kepada orang yang mempunyai kompetensi dalam menjawab persoalan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah dengan memohon penjelasan tentang status hukum suatu masalah atau perbuatan yang belum ada ketetapan hukumnya. Status hukum inilah yang dimaksudkan sebagai fatwa. Fatwa sangat dibutuhkan umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (faao’idl), batasan-batasan (hudud) serta menyatakan tentang halal atau haramnya sesuatu. Berbagai persoalan baru yang muncul, menuntut setiap orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang hukum Islam untuk mengeluarkan fatwa sebagai upaya memberikan rasa ketenangan dan kepastian bagi umat Islam dalam menjalankan suatu perbuatan yang status hukumnya belum jelas.
Fatwa pada masa sekarang ini nampaknya sulit dilakukan oleh individu atau perseorangan, karena mengingat banyaknya persoalan yang muncul tidak mungkin bisa diselesaikan seorang saja. Selain memang, seperti disebutkan di atas, persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid sangatlah berat. Maka, melalui sebuah lembaga yang kompeten, para ahli agama Islam akan saling bahu-membahu dalam menentukan hukum atas persoalan yang berkembang di masyarakat dan butuh segera untuk dicarikan jawaban dan solusinya. Di sinilah relevansi dan nilai penting keberadaan lembaga untuk memberikan fatwa yang bersifat kolektif ( al-fatwa al-Jama’iy), yang kebetulan di Indonesia, lembaga yang dianggap mempunyai kompetensi dan reperesentasi untuk mengeluarkan fatwa adalah Majlis Ulama indonesia (MUI). Fatwa mempunyai kekuatan hukum yang tidak mengikat (ghairu ilzamin). Sungguh pun demikian, fatwa menjadi bahan pertimbangan penting bagi umat Islam di mana pun berada. Berbagai penelitian menunjukkan, di Indonesia fatwa mempunyai peran penting dalam memengaruhi pilihan dan sikap masyarakat atas berbagai persoalan yang sedang terjadi. Di beberapa negara Islam, fatwa resmi yang dikeluarkan pemerintah malah bersifat mengikat dan ada sanksi hukumnya.
E. Prosedur dan Persyaratan Fatwa Dalam Hukum Islam
Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dengan upaya serius, para mufti atau mujtahid memberikan fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, kaitan antara ijtihad dengan fatwa sangat erat sekali, sebab ijtihad itu merupakan suatu usaha yang masksimal para ahli untuk mengambil atau meng-istinbath-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu salah satu hasil dari ijtihad itu sendiri. Hukum Islam yang berlandaskan al-Qur`an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yangdituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan. Karena begitu penting nilai fatwa dalam kehidupan keagamaan umat Islam, dalam mengeluarkan fatwa, seorang mufti atau lembaga tertentu harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang cukup ketat, yang telah ditetapkan oleh para ulama’. Hal ini diberlakukan untuk menghindari kecacatan dan kesalahan dalam mengeluarkan fatwa.
KH Ma’ruf Amin (21:2007) yang kini menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus yang membidangi masalah fatwa dan hukum Islam mennjelaskan 5 hal atau rukun yang berkaitan dengan proses dikeluarkannya fatwa yakni:
- Al-ifta atau kegiatan menerangkan hukum sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- Al- Mustafti atau individu atau kelompok yang meminta fatwa,
- Mufti atau orang dan istitusi yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Mustafti fihi atau masalah yang dipertanyakan dan ingin dicarikan status hukumnya.
- Dan fatwa itu sendiri sebagai jawaban hukum atas masalah yang ditanyakan. Kelima hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penetapan fatwa.
Fatwa tidak bisa dikeluarkan tanpa prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan, serta disepakati para ulama. Ia menempati posisi penting dalam hukum Islam karena statusnya sama dengan hasil ijtihad. Realitas dan fenomena permintaan fatwa dari individu atau masyarakat sudah ada semenjak awal sejarah perkembangan umat Islam. Pada masa Rasulallah SAW, ketika para sahabat menemukan persoalan yang dianggap sulit untuk dicarikan solusinya dan jawabannya, mereka langsung bertemu dan meminta jawaban dari Nabi Muhammad SAW, meskipun jawaban nabi langsung berupa nash-nash al-Qur’an dan Hadist Nabi sendiri, tetapi tradisi permintaan, konsultasi, bimbingan untuk menjawab berbagai persoalan hidup kepada ahlinya merupakan bagian spirit yang menginspirasi munculnya tradisi fatwa dalam masyarakat muslim. Keberadaan Nabi SAW pada masa itu adalah pembuat keputusan (decision maker) dan pemegang kebijakan bagi hampir seluruh persoalan umat Islam. Setelah kewafatan Nabi, pemegang otoritas keagamaan menjadi persoalan. Untuk itu, para ulama selalu membuat prosedur dan persyaratan dalam berbagai hal yang menyangkut penentuan panduan keagamaan, termasuk persoalan fatwa. Untuk itu, para ulama memberikan persyaratan bagi mufti, diantaranya sebagai berikut:
- Seseorang yang ingin mengelurkan fatwa keagamaan harus memahami ajaran Al- Qur’an secara mendetail, lengkap dengan kemampuan menafsirkan dan menganalisisnya secaraa tajam.
- Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara seksama tentang asbabunnuzul al Qur’an dan mengetahui juga asbabul wurud hadist Rsulullah saw.
- Seseorang ahli fatwa harus mengetahui ayat-ayat yang nasikh dan ayatayat yang mansukh
- Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara persis tetang ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih.
- Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara detail tentang aspek-aspek yang menyangkut penta’wilan Al Qur’an dan penafsirannya.
- Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara detail tentang hadist-hadist Rasulullah saw.
- Seorang ahli fatwa harus mengetahui tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah.
- Seorang ahli fatwa harus mengetahui tentang ilmu-ilmu agama Islam secara menyeluruh, seperti ilmu fiqh, Ushul Fiqh, ilmu kalam, ilmu nahwu dan shorof, balaghah, dan ilmu-ilmu lain yang sifatnya untuk menunjang kelengkapan dan memberikan fatwa keagamaan.
- Seorang ahli fatwa juga termasuk orang harus mengetahui tentang kepentingan masyarakat banyak (masalahatul mursalah)
- Seorang ahli fatwa harus terhindar dari sikap dan watak vested interest, namun mengutamakan kepentingan ilmiah semata-mata demi kepentingan ummat manusia, khususnya ummat Islam (Abdul Hadi Fatah, 37-38:1991).
Selain persyaratan di atas, Imam Ahmad bin Hambal seperti yang dikutip Ma’ruf Amin (30:2007) menyatakan bahwa seseorang tidak pantas untuk mengeluarkan fatwa sebelum pada dirinya terdapat lima hal berikut;
Pertama, mempunyai niat yang tulus ikhlas, maksudnya setiap orang yang mengeluarkan fatwa harus diniatkan lillahi ta’ala, tidak karena maksud-maksud lain, apalagi maksud keduniaan, misalnya agar mendapatkan kedudukan yang mulia. Kedua, mempunyai ketenangan dan kewibawaan. Setiap mufti harus mampu menyampaikan dan menjelaskan fatwanya kepada pihak yang meminta fatwa, sehingga fatwanya dipahami secara utuh dan benar. Orang yang tidak mempunyai ketenangan dan kewibawaan akan kesulitan untuk menyampaikan secara jelas fatwanya. Ketiga, mempunyai kapasitas keilmuan yang memadai untuk menetapkan fatwa, karena tanpa kapasitas ini, seorang akan cenderung melakukan tahakum membuat-buat hukum. Keempat, mempunyai penghidupan (ma’isyah) yang cukup. Dankelima, mempunyai kecerdikan dan kecermatan dalam menghadapi masalah. Hal ini diperlukan, karena mufti harus memahami berbagai persoalan yang diajukan oleh peminta fatwa termasuk kemungkinan dari orang yang berniat jahat kepadanya.
Imam Nawawi, seperti yang juga dikutip Ma’ruf Amin (35:2007) menjelaskan bahwa; pertama, berfatwa hukumnya adalah fardlu kifayah. Jika ada seseorang atau pihak yang menanyakan hukum sesuatu, maka wajib bagi orang yang mempunyai kompetensi berfatwa untuk menjawabnya. Dan jika ada orang lain yang juga mempunyai kompetensi untuk menjawabnya, maka menjawabnya adalah fardlu kifayah. Kedua, jika suatu fatwa telah dikeluarkan akan tetapi ada sesuatu hal dirasa tidak sesuai, maka pihak yang mengeluarkan fatwa harus memberikan pemberitahuan dan penjelaskan kepada pihak yang meminta fatwa, bahwa fatwanya tidak sesuai. Ketiga, diharamkan bagi mufti untuk mempermudah untuk mengeluarkan fatwa, dan begitu pula haram untuk meminta fatwa kepadanya. Keempat, seorang mufti harus sehat lahir dan batin ketika mengemukakan fatwanya, sehingga ia berfikir jernih dan menjaga netralitasnya dalam menentukan hukum suatu masalah. Kelima, seorang mufti dilarang untuk menjadikan berfatwa sumber penghidupan dan penghasilan untuk kepentingan dirinya. Keenam, penetapan fatwa harus merujuk kepada ulama madzhab tertentu yang didasarkan kepada kitab-kitab yang mu’tabarah. Ketujuh, pengulangan penetapan fatwa harus disesuaikan dengan illat dan argumentasinya.Kedelapan, penetapan fatwa harus jelas dan langsung dapat dilaksanakan oleh peminta fatwanya.
F. Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam
Fatwa adalah penjelasan hukum Islam atas suatu persoalan yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan bagian dari term hukum Islam yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, maka, kaedah pengambilan fatwa tidak berbeda dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, seorang mufti sama kedudukannya dengan seorang mujtahid.
Fungsi fatwa adalah memberi jawaban hukum atas pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum yang tidak diketemukan dalam al-Quran maupun sunnah atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran hukum Islam. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Seorang yang memberi Fatwa (Mufti) harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, seperti memahami pelbagai aspek hukum Islam dan dalil yang menopangnya dan otoritas keilmuannya diakui oleh masyarakat, sehingga masyarakat datang kepadanya untuk meminta pertimbangan hukum. Dalam hal ini, dan karena dirasa terlalu sulitnya memperoleh kewenangan fatwa, dalam konteks Indonesia, maka lazim diberikan lembaga khusus dalam sebuah organisasi, misalnya Komisi Fatwa MUI, Bahtsul Masail NU, Majlis Tarjih Muhammadiyah dan lainnya yang dianggap mempunyai komptensi yang memadai. Meskipun, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut juga mendapat tanggapan yang bervariasi, pro dan kontra, termasuk MUI yang dianggap sebagai lembaga yang merepresentasikan keberadaan ulama-ulama di Indonesia. Realitas ini menjadi bahan kajian, bahwa menentukan penetapan fatwa itu tidak mudah dan membutuhkan pertimbangan yang komprehensif.
Menjadi keprihatinan bersama dengan fenomena maraknya orang atau lembaga yang dengan mudah mengeluarkan fatwa. Satu sisi seringkali masyarakat muslim Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa fatwa yang keluar dari lembaga agama yang resmi seperti MUI sering menimbulkan perdebatan panjang sehingga menimbulkan pro dan kontra, bahkan terkadang fatwa itu dimentahkan oleh segelintir orang yang tidak kompeten dalam bidang hukum Islam, pada sisi yang lain masyarakat menanti jawaban MUI atas berbagai persoalan yang ditanyakan kepada lembaga tersebut. Akibatnya, masyarakat sering bingung dan tidak bisa menentukan mana yang benar diantara berbagai pendapat tersebut. Menurut Zain al-Najah, fatwa itu adalah hak ulama, bukan perorangan. Dan yang mengerti urusan fatwa adalah mereka-mereka yang tahu dan mengerti secara baik hukum Islam. Karenanya, jika ada orang meskipun dikenal tokoh Islam, tapi bukan berlatar belakang hukum Islam atau fiqih, mereka tak memiliki hak mengeluarkan fatwa. Menurut Zain al-Najah memang aneh, setiap ada fatwa MUI, semua media massa termasuk TV justru meminta komentar tokoh-tokoh yang tak ahli dalam hukum Islam. Seharusnya media massa dan televisi mengerti kepada siapa harus mendapat komenetar tentang fatwa, tidak kepada orang yang tidak mengerti tentang fatwa. Menurutnya, bila dibandingkan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, belum ada dalam sejarahnya fatwa ulama dikencam apalagi dilecehkan orang-orang awam dan bukan ahli di bidangnya kecuali di Indonesia. Ia mencontohkan, dalam kasus semua fatwa yang dikeluarkan Darul Ifta’ al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) atauMajma’ul Buhuts al-Islamiyyah di Al-Azhar, tak pernah masyarakat bahkan pihak pemerintah mempertanyakan atau mengotak-atiknya.Umumnya, semua masarakat Mesir paham dan menghormati, bahkan termasuk pihak pemerintah. Hal ini nampaknya berbeda dengan di Indonesia di mana fatwa ulama ‘dilecehkan’ orang yang tak paham hukum Islam[1].
Realitas pro dan kontra terhadap berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, seyogyanya harus lebih dipahami sebagai bentuk dinamika intelektualitas yang menghargai sebuah perbedaan, daripada pelecehan terhadap keberadaan fatwa MUI. Kedudukan fatwa MUI yang tidak mengikat semua masyarakat atau warga memberikan peluang orang atau lembaga untuk memberikan respon yang bervariasi, mulai dari yang mengkritik, berupaya menjelaskan, menerima dan menolak total terhadap keberadaan fatwa MUI. Pro dan kontra ini juga bisa dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap kedua belah pihak yaitu MUI dan stakholdernya, baik yang pro maupun yang kontra. Paling tidak bagi yang pro, MUI dianggap sebagai lembaga yang merepresentasikan ulama-ulama yang ada di Indonesia, yang mempunyai kompetensi untuk memberikan fatwa. Sementara bagi yang kontra menganggap fatwa MUI bermasalah; proses pendefinisian masalah, prosedur penetapan fatwa, dan kelayakan kompetensi anggota komisi fatwa MUI sebagai seorang mufti. Misalnya dalam fatwa pluralisme agama, MUI sebenarnya mengharamkan pluralisme agama yang didefinisikan oleh MUI sendiri, padahal pluralisme diluar MUI mempunyai definisi dan pengertian yang berbeda dengan yang didefinisikan MUI. Maka sebenarnya MUI mengharamkan pandangan MUI tentang pluralisme, bukan pluralisme yang dipahami oleh kalangan lain.
Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia Sejarah Hukum Islam di Indonesia
Mengapa Harus memilih KHK Law Office sebagai Advokat/Pengacara di Yogyakarta?
- Pelayanan Simple dan Cepat.
- Expert/Ahli dan Terpercaya. Kami KHK Law Office telah berpengalaman dan tentunya ahli dibidangnya serta dapat dipercaya.
- Harga Terjangkau dan layanan 24 Jam. Dengan harga terjangkau, namun pelayanan tetap yang terbaik. Dan tentunya, layanan konsultasi hukum 24 jam.
Wilayah hukum diluar Kalimantan, Jasa Pengacara Jogja: